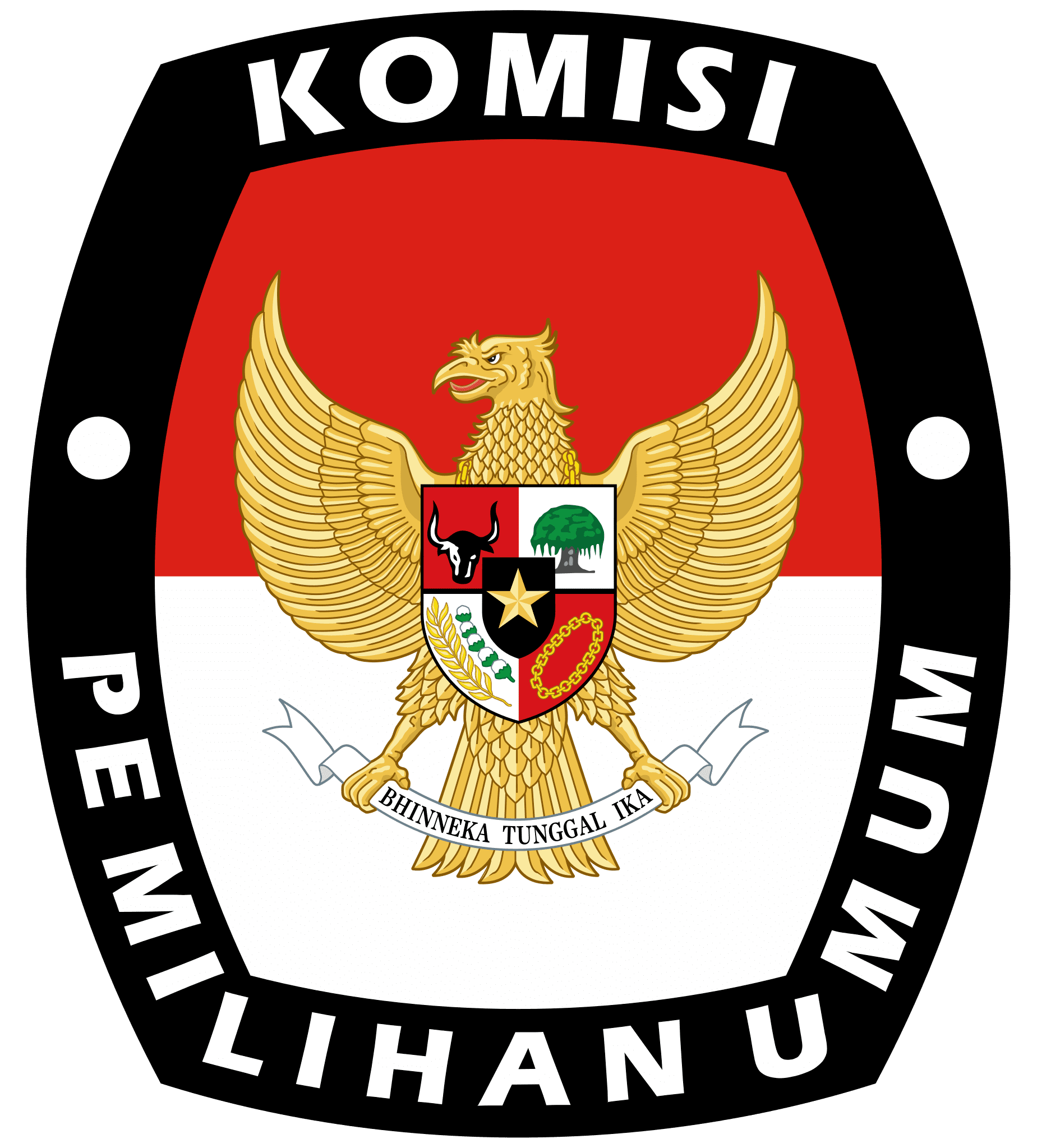Santri dan (Tradisi) Demokrasi
Oleh: M Afifuddin
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Di tengah kesalahpahaman sebagian pihak terhadap praktik kehidupan di pesantren, negara melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
Penetapan ini merupakan penghormatan negara terhadap kiprah kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa.
Menanggapi kondisi negeri hari ini, terutama terkait pesantren, penulis yang juga kaum santri teringat dengan artikel KH Abdurrahman Wahid, ”Pesantren sebagai Sub-Kultur” (1974). Artikel ini memiliki relevansi saat kini, di tengah kesalahpahaman terhadap kultur pesantren yang dinilai feodalistik dan antidemokrasi.
Artikel Gus Dur pada dekade awal Orde Baru itu melakukan koreksi terhadap kesalahpahaman pemerintah terhadap pesantren waktu itu. Atas nama pembangunan dan modernisasi, pesantren dinilai sebagai lembaga dan kultur keislaman yang terbelakang serta menghambat pembangunan. Kultur yang berorientasi pada keakhiratan, serta model kepemimpinan kiai yang patronatif menjadi argumentasi bagi penilaian kemunduran ini.
Gus Dur melalui artikel tersebut mengoreksi kesalah-bacaan teknokratisme Orde Baru itu. Melalui metode interpretivisme simbolik dalam studi budaya, Gus Dur sebagai santri melakukan penafsiran dari dalam kultur pesantren yang tidak bisa dilakukan kaum luar.
Ia lalu menggunakan konsep subkultur untuk menjelaskan kultur pesantren yang unik. Subkultur Gus Dur definisikan sebagai sub dari kultur mayoritas yang terpisah, unik, independen, tetapi bisa memengaruhi kultur mainstream tersebut. Terdapat tiga ciri utama subkultur pesantren menurut Gus Dur.
Pertama, sistem nilai yang unik yang mengacu pada asketisisme berdasarkan sistem keilmuan Islam yang Gus Dur sebut fiqh-sufistik. Sistem keilmuan fiqh-sufistik mengacu pada penggabungan fiqh (hukum Islam) dan tasawuf (spiritualitas). Ini memuat dua prinsip kehidupan sekaligus, yakni rasional dalam tata sosial dan spiritual pada level personal. Sistem fiqh-sufistik ini melahirkan kaum santri yang rasional dalam konteks hukum, tetapi asketik dalam orientasi hidup. Asketisisme ini yang salah dipahami pemerintah Orde Baru karena tidak berorientasi keduniawian.
Kedua, perilaku yang unik, yang lahir dari sistem nilai unik tersebut. Misalnya, pembagian waktu yang mengikuti proses belajar-mengajar (pengajian) dan jadwal shalat. Hal ini membuat kaum santri aktif di malam hari karena seharian sibuk mengaji. Termasuk dalam hal ini ialah penghormatan kepada kiai sebagai ahli ilmu agama karena para santri mengutamakan ilmu agama demi kesuksesan di dunia dan akhirat.
Ketiga, model kepemimpinan kiai yang unik. Di pesantren, kiai diposisikan tidak hanya sebagai guru atau dosen, tetapi juga pembimbing intelektual dan spiritual. Ruang lingkup pengajaran kiai tidak terhenti pada ilmu pengetahuan, tetapi juga kematangan spiritual. Inilah yang membuat kiai sangat ”powerful” bagi santri karena ia melingkupi keseluruhan hidup santri. Bahkan, ketika para santri telah lulus dari pesantren.
Subkultur kenegaraan
Berdasarkan penjelasan Gus Dur ini, maka penilaian terhadap pesantren tidak bisa parsial, tetapi mesti menyeluruh melalui perspektif subkultur ini. Sebab, pada ranah kebangsaan dan kenegaraan, subkultur pesantren berperan besar dalam kemerdekaan, pendirian negara, dan keberlangsungan bangsa ini. Peran inilah yang dipahami oleh pemerintah sehingga menetapkan Hari Santri Nasional sebagai salah satu bukti pengakuan.
Menariknya, subkultur pesantren tidak hanya beroperasi di dalam pesantren, tetapi juga pada ranah kebangsaan dan kenegaraan. Pada masa kritis menjelang penetapan dasar negara sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, Kiai Wahid Hasyim, abah Gus Dur, menggunakan logika subkultur dalam mengatasi krisis tersebut. Logika itu ialah kaidah fiqh (legal theory) yang digunakan untuk merespons dorongan Bung Hatta agar kelompok Islam mau menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pengganti ”tujuh kata” Piagam Jakarta.
Kiai Wahid menggunakan kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Artinya, ’apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan ditinggalkan prinsip dasarnya’. Dalam konteks itu, ketika syariah Islam gagal diterapkan dalam dasar negara, maka keberadaan nilai tauhid dalam sila Ketuhanan YME membuat umat Islam tidak boleh meninggalkan dasar negara itu. Dengan demikian, berdasarkan pemaknaan bahwa sila Ketuhanan YME adalah tauhid, Kiai Wahid membangun argumentasi bagi kelompok Islam agar menerima Pancasila, bukan Piagam Jakarta.
Bayangkan jika tidak ada argumentasi Kiai Wahid, maka kita tidak akan memiliki Pancasila dengan sila Ketuhanan YME, yang bagi umat Islam bermakna tauhid, tetapi pada saat bersamaan, terbuka bagi semua agama untuk memiliki sila ketuhanan yang inklusif tersebut.
Dalam konteks pemikiran politik, kaum santri juga menggunakan logika subkultur yang unik. Ketika sebagian besar khazanah Islam mengabaikan hak asasi manusia (HAM), tradisi pesantren justru menjadikan HAM sebagai parameter utama dari tujuan utama syariah (maqashid al-syari’ah). Hak hidup dan hak berpikir menjadi nilai-nilai utama, di samping hak beragama, kehormatan, dan kepemilikan. Atas dasar HAM inilah, para pemikir pesantren merekomendasikan demokrasi sebagai satu-satunya sistem politik yang mampu menjamin tujuan syariah tersebut.
Ini yang membentuk pandangan dunia Islam (Islamic world view) yang menyatukan tiga ide, yakni demokrasi (syura), persamaan (musawah), dan keadilan (’adalah). Demokrasi merupakan sistem utama yang menopang prinsip persamaan warga negara di hadapan hukum demi tegaknya keadilan sosial. Berdasarkan pandangan dunia Islam ini, maka kalangan pesantren justru menolak Negara Islam karena rawan terhadap pelanggaran nilai-nilai demokrasi, persamaan hukum, dan keadilan sosial.
Bagi kalangan Islamis, logika ini tentu di luar konsep umum politik Islam karena terkesan menolak formalisme Islam. Sedangkan bagi teori politik sekuler, logika ini juga ”di luar nalar” karena menggunakan argumen agama dalam menguatkan demokrasi.
Atas sumbangan pemikiran, sikap politik, dan gerakan kebangsaan dari kaum pesantren inilah, maka antropolog seperti Robert W Hefner dalam Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia (2000) telah lama menempatkan pesantren sebagai ”lumbung intelektual” bagi kuatnya ”Islam sipil” (civil Islam) di Indonesia. Sebuah corak keislaman demokratik yang sangat dibutuhkan untuk menguatkan demokratisasi di negeri Muslim terbesar ini.
Jihad demokrasi
Dalam rangka Hari Santri Nasional 2025, kaum santri memang perlu menguatkan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Resolusi Jihad yang pernah dideklarasikan Hadlratus Syeikh KH Hasyim Asy’ari untuk melawan penjajah perlu dikontekstualisasikan untuk membangun negara, terutama dalam konteks penguatan demokrasi.
Kualitas demokrasi kita memang masih berdinamika. Menurut sorotan internasional, yakni survei Indeks Demokrasi Global oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) 2024, demokrasi Indonesia terkategori sebagai demokrasi cacat (flawed democracy) dengan skor 6,44. Kelemahan dalam budaya politik (civic culture) dan kebebasan sipil (civil liberties) menjadi penyebab kecacatan itu. Meksipun dalam tilikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi kita justru mengalami kenaikan dari 79,51 poin (2023) menjadi 79,81 poin (2024). Akan tetapi kita memang sepakat untuk terus menaikkan kualitas demokrasi kita.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan berbagai upaya untuk menguatkan kualitas demokrasi kita. Pada level penguatan budaya politik, KPU telah menginisiasi berbagai program pendidikan politik dan literasi pemilih berkelanjutan. Misalnya pendirian Akademi Pemilihan Umum, hingga literasi pemilu melalui pendekatan budaya popular bagi "Gen Z" di era digital.
Kampanye larangan penggunaan politik identitas juga terus digaungkan, termasuk menghindari dan melawan berita bohong (hoaks), politik uang (vote buying). KPU juga melakukan terobosan dengan mengkaji partisipasi masyarat dalam Pemilu dan Pilkada dalam bentuk Indeks Partisipasi Pemilu (IPP). Sebagai salah satu negara mayoritas muslim, penting bagi kita untuk memastikan bahwa praktik Pemilu dan Pilkada yang baik kompatibel dengan nilai-nilai agama (Islam).
Dalam kaitan ini, kaum santri penting terlibat, terutama dalam menguatkan budaya politik, budaya demokrasi, dan budaya kewargaan. Hal ini memang telah dilakukan sejak lama oleh kalangan Muslim tradisionalis ini, melalui pengarusutamaan nilai-nilai Islam moderat yang selaras dengan demokrasi, Pancasila dan kebangsaan.
Hanya saja, peran kebangsaan yang telah mentradisi ini perlu diletakkan dalam konteks pelaksanaan demokrasi elektoral (pemilu), di mana kaum santri juga bisa berperan sebagai pemilih, peserta, bahkan juga penyelenggara. Praktik pemilu yang baik dengan peran kita sebagai apa pun sejatinya merupakan salah satu cara kita menjaga nilai dan kultur demokrasi yang kompatibel dengan nilai-nilai kaum santri. Sekali lagi, Selamat Hari Santri Nasional!
M Afifuddin, Santri, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
![]()
![]()
![]()